Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Pemerintah dihadapkan pada sebuah persoalan pelik dalam penyelesaian honorer pascapemberlakuan UU Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Rumitnya persoalan tersebut dipicu adanya pengaturan mengenai penyelesaian status honorer yang saat ini bekerja di sejumlah unit pemerintah.
Disebutkan pada Pasal 66 bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak UU ini mulai berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN.
Pasal tersebut memberikan amanat kepada pemerintah untuk segera menuntaskan status para honorer yang selama ini bekerja di instansi pemerintah. Salah satu solusi yang akan diambil adalah konversi status kepegawaian para honorer menjadi PPPK. Alternatif lain yang bisa dipilih adalah pemberhentian para honorer melalui mekanisme pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Buah simalakama bagi pemerintah mengingat kedua alternatif yang tersedia memiliki konsekuensi yang cukup memusingkan. Apabila konversi status menjadi PPPK dipilih maka berdampak terhadap penyediaan anggaran yang cukup besar.
Sebagai ilustrasi seorang honorer yang selama ini memperoleh penghasilan di angka ratusan ribu per bulan, pascamenjadi PPPK penghasilan yang diterima akan melonjak sesuai besaran tabel gaji PPPK. Gaji yang diterima masih akan ditambah lagi dengan berbagai tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Tampaknya pertimbangan beban anggaran ini yang membuat pemerintah harus menyusun berbagai simulasi untuk menyelesaikan sisa honorer yang masih ada. Termasuk munculnya PPPK paruh waktu untuk menyiasati bengkaknya anggaran yang harus disiapkan.
Opsi melakukan PHK jelas bukan sesuatu yang bijak saat ini. Meskipun secara teori dapat dilakukan namun secara praktik menjadi rumit tatkala dihadapkan pada pertimbangan yang bersifat emosional.
Penyelesaian honorer bukan merupakan hal yang baru, pengangkatan honorer menjadi PNS pernah dilakukan secara besar-besaran pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hanya saja kebijakan tersebut dihentikan ketika ditemukan fakta bahwa pascapengangkatan, jumlah honorer bukannya berkurang namun memiliki kecenderungan tetap bahkan bertambah di sejumlah wilayah.
Merupakan sebuah hal yang logis ketika sebagian orang memilih menjadi honorer sebagai salah satu cara untuk menjadi ASN. Pertimbangannya cukup sederhana, menjadi ASN melalui jalur seleksi bukan hal yang mudah dilakukan.
Berbagai tahapan ujian harus dilalui plus penggunaan perangkat komputer secara real time dalam menilai hasil ujian adalah momok yang ditakuti sebagian orang. Alhasil jalur honorer lebih menjanjikan meskipun secara finansial besaran upah yang diterima ala kadarnya.
Apabila merujuk pada UU ASN, masalah kepegawaian yang diatur di dalam undang-undang tersebut sangat kaku dengan membatasi hanya ada dua jenis kepegawaian yaitu PNS dan PPPK. Tidak ada jenis kepegawaian lain yang bekerja di institusi pemerintah selain kedua kelompok tersebut. Pembatasan jenis kepegawaian tersebut didasarkan pada pertimbangan agar institusi pemerintah tidak menggemuk melalui penambahan pegawai selain PNS maupun PPPK.
Apakah dengan pemberlakuan larangan pengangkatan pegawai non-ASN atau honorer mampu meredam penambahan pegawai di institusi pemerintah? Jawabannya bisa ya atau tidak. Panjangnya proses untuk mendapatkan tambahan SDM pada institusi pemerintah memungkinkan larangan tersebut untuk tidak dipatuhi sepenuhnya. Terdapat potensi untuk merekrut pegawai baru dengan berbagai istilah yang sengaja diciptakan untuk menyiasati regulasi yang ada.
Fenomena honorer cenderung terjadi pada lingkup pemerintah daerah dibandingkan pemerintah pusat. Khusus penyelesaian secara tuntas honorer di daerah maka pertimbangan ketersediaan anggaran harus menjadi acuan.
Pada lingkup honorer di daerah, penggunaan metode berupa kemampuan fiskal atau anggaran dapat dijadikan sebuah terobosan untuk menyelesaikan permasalahan honorer saat ini atau di masa depan.
Metode ini selaras dengan pengaturan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 146 undang-undang tersebut diatur batas maksimal belanja pegawai yaitu 30% dari APBD, jika saat ini masih di atas angka 30% maka wajib diturunkan proporsinya paling lambat pada 1 Januari 2027.
Mencapai target belanja pegawai pada angka 30% dari APBD akan menjadi tantangan bagi sejumlah daerah terutama jika saat ini alokasi belanja pegawai masih melebihi 30%. Secara rata-rata nasional, belanja pegawai di pemda berada pada angka 37% dari APBD masing-masing.
Selain berkaitan dengan kemampuan fiskal, terdapat dua faktor yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan honorer. Pertama berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan kedua berkaitan dengan pemberian kewenangan pengangkatan pegawai kepada pemda.
Kebijakan akuntansi berkaitan dengan pencatatan seluruh belanja berkaitan dengan pemberian penghasilan bagi pegawai hanya pada satu jenis belanja yaitu belanja pegawai. Bagi pegawai berstatus PNS maupun PPPK pembebanan penghasilannya dialokasikan dan dicatat sebagai belanja pegawai.
Sedangkan bagi pegawai honorer beban penghasilannya dicatat dalam belanja barang atau belanja modal. Sangat bergantung pada program atau kegiatan apa pegawai honorer tersebut menginduk.
Jika seluruh pembebanan penghasilan menyatu dalam belanja pegawai maka akan memberikan gambaran utuh seberapa besar proporsi beban gaji sebenarnya yang ditanggung APBD. Sehingga ketika berbicara batas maksimal 30% APBD maka sudah mencakup seluruh unsur pegawai di dalamnya. Hal ini tentu akan mengurangi minat pemda untuk menyiasati istilah demi menambah pegawai baru.
Kedua berkaitan dengan desentralisasi kewenangan pengangkatan pegawai khususnya PPPK. Salah satu pembeda antara PNS dan PPPK adalah mutasi kepegawaian. PNS dapat dimutasi ke manapun termasuk dari pusat ke daerah atau sebaliknya, sedangkan PPPK tidak dapat dimutasi.
Selama ini mekanisme pengangkatan pegawai diawali dari pengusulan kebutuhan oleh pemda ke pemerintah pusat, selanjutnya pemerintah pusat memberikan persetujuan berupa formasi pegawai. Persetujuan pemerintah pusat atas usulan pemda akan diperhitungkan dengan penambahan anggaran pada Dana Alokasi Umum.
Mekanisme ini memiliki kelemahan karena seberapapun usulan yang diajukan pemda serta formasi yang disetujui, besaran DAU yang diberikan akan bertambah sesuai dengan penambahan pegawai.
Penambahan DAU selaras dengan rumus perhitungan dimana salah satu unsurnya yaitu jumlah gaji ASN daerah. Secara sederhana ketika terjadi penambahan ASN di daerah maka DAU yang diterima oleh pemda pun akan bertambah.
Hal ini yang kemudian mendorong pemda untuk tetap membuka lowongan bagi honorer, karena bagaimanapun ketika honorer tersebut mengalami perubahan status maka beban belanjanya akan ditambahkan pada DAU yang akan diterima.
Dari kedua faktor tersebut sebenarnya dapat dipertimbangkan untuk melakukan desentralisasi pengangkatan PPPK menjadi kewenangan pemda. Pembagian kewenangan dengan pemda lebih mendominasi pada jenis kepegawaian PPPK diharapkan dapat meningkatkan peran dan tanggung jawab pemda khususnya terkait dalam penyediaan anggaran bagi pembayaran penghasilan.
Atas adanya tambahan kewenangan tersebut, pemerintah pusat dalam pengalokasian DAU dapat melakukan moratorium penyesuaian formula khususnya pada komponen jumlah gaji ASN daerah.
Kesimpulannya adalah ketika pemda berani mengambil keputusan untuk mengangkat pegawai honorer (atau alih status menjadi PPPK) beban anggaran sudah harus tersedia secara mencukupi dengan tetap mempertimbangkan batas maksimal alokasi belanja pegawai sebesar 30% dari APBD.
(miq/miq)

 4 weeks ago
15
4 weeks ago
15
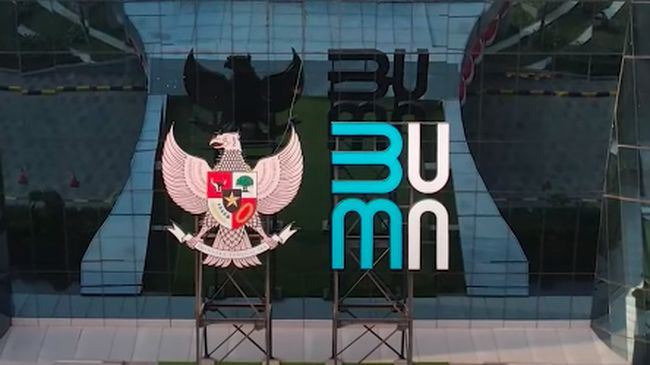









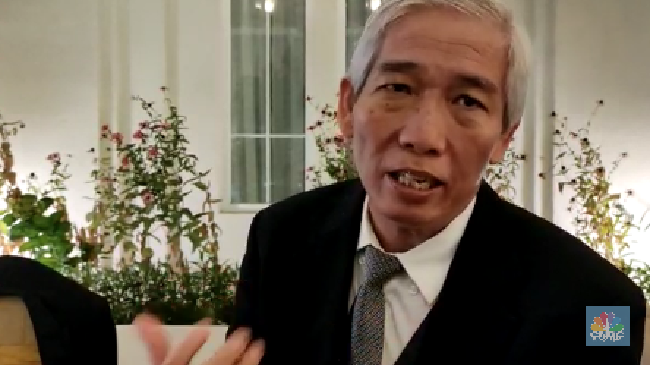



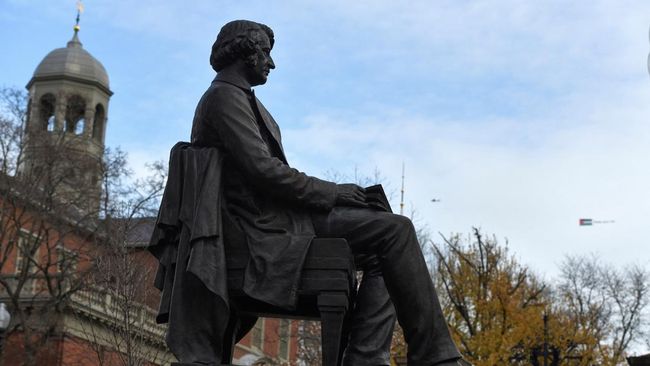

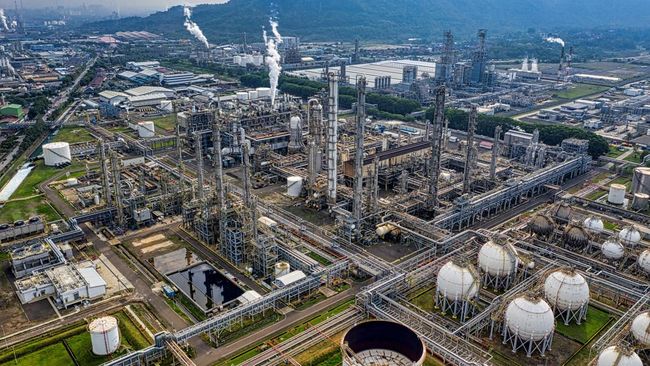








:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5106825/original/004690100_1737626093-WhatsApp_Image_2025-01-23_at_15.17.14.jpeg)






:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5060424/original/012183800_1734756388-1734752130220_tips-puasa-untuk-anak.jpg)







:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5051207/original/080163400_1734234398-pexels-bertellifotografia-29509460.jpg)



