Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Lagu kebangsaan kita menyapa dengan ajakan yang sederhana namun berisi: "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya." Ungkapan itu tidak sekadar seruan kemerdekaan, sisi lain yang tersirat dari lagu kebangsaan Indonesia, yaitu filosofi pembangunan yang tak lekang oleh waktu.
Perubahan besar selalu bermula dari dua hal, kesadaran pemikiran dan tindakan. Kesadaran yang dimaksud adalah kita harus memandang masa depan secara berbeda dan kita harus membangun pondasi yang kuat untuk melangkah lebih dekat ke tujuan.
Hari ini, ketika ekonomi global bergerak menuju era hijau, ajakan itu menemukan makna baru. Indonesia mesti membangun "jiwa energi hijau" berupa mindset, visi, dan arah berpikir yang baru serta membangun "badan energi hijau" berupa infrastruktur, industri, dan kebijakan nyata yang menopangnya.
Selama puluhan tahun kita tumbuh dengan energi fosil yang berperan sebagai tulang punggung pembangunan. Batu bara dan minyak bumi menjadi bahan bakar negeri ini, menggerakkan pabrik, pelabuhan, rumah-rumah di pelosok Indonesia.
Energi konvensional membangun ekonomi kita, namun juga menjerat kita dalam ketergantungan, dan berpotensi menghimpit perekonomian negara apabila harga minyak global bergejolak dan inflasi melejit. Namun kini dunia berubah, dan perubahan itu mulai bergerak menjauh dari sumber energi konvensional dan beralih ke energi bersih.
Transisi menuju energi bersih bukan lagi sekadar isu moral atau lingkungan, melainkan isu ekonomi dan kedaulatan nasional. Rantai pasok energi global tengah didesain ulang terutama karena dinamika energi global dan Indonesia harus memiliki posisi yang strategis di tengah perubahan ini.
Untuk menjadi bagian dari masa depan itu, kita tidak bisa hanya mengganti sumber daya, kita harus juga mengubah cara berpikir. Membangun jiwa berarti memahami bahwa energi hijau bukan proyek lingkungan semata, tetapi proyek peradaban. Energi bersih bukan beban, melainkan merupakan kesempatan untuk menulis ulang model pembangunan nasional.
Kesadaran seperti ini penting karena kita tengah menyaksikan pergeseran paradigma. Laporan McKinsey & Company Global Energy Perspective 2025 menyebut bahwa ekonomi global kini memasuki fase pragmatisme energi, di mana keamanan pasokan dan keterjangkauan menjadi sama pentingnya dengan keberlanjutan.
Negara yang berhasil bukan hanya yang paling cepat menutup Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), tetapi yang paling mampu menyeimbangkan tiga variabel: energi yang murah, stabil, dan bersih. Di sinilah peluang besar muncul untuk Indonesia.
Sebagai negara tropis dengan garis khatulistiwa sepanjang ribuan kilometer, kita memiliki potensi energi surya nyaris tak terbatas. Kita juga memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia, kekuatan arus laut yang bisa diubah menjadi listrik, serta biomassa dari hutan tropis dan limbah pertanian. Sumber-sumber itu ada, tetapi belum sepenuhnya diberdayakan.
Membangun jiwa energi hijau berarti melihat semua potensi tersebut bukan sebagai data statistik, tetapi sebagai aset strategis yang harus diubah menjadi nilai ekonomi. Energi hijau bukan hanya soal mengurangi emisi, tetapi membuka lapangan kerja, memperkuat industri lokal, dan memperbaiki neraca perdagangan.
Namun jiwa tanpa tubuh hanyalah niat tanpa arah. Setelah mindset terbentuk, Indonesia harus membangun badan dari energi hijau berupa infrastruktur nyata. Badan ini bukan hanya mencakup pembangkit surya atau turbin angin, tetapi juga sistem yang menghubungkannya.
Sistem yang harus dibangun di antaranya adalah jaringan transmisi yang kuat, sistem penyimpanan energi yang efisien, kebijakan fiskal yang mendukung, dan model bisnis yang menarik bagi investor.
Program Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$ 20 miliar yang disepakati tahun lalu adalah langkah besar, namun implementasinya berjalan lambat. Investasi belum mengalir optimal, birokrasi masih kompleks, aturan saling tumpang-tindih, dan ketidakpastian harga jual listrik hijau masih membayangi.
Padahal jika sistem ini diperbaiki, hasilnya bisa luar biasa. Potensi tenaga surya di Indonesia diperkirakan lebih dari 200 gigawatt, namun saat ini yang baru dimanfaatkan sekitar 0,1 persen. Panas bumi baru dimanfaatkan seperempat dari kapasitas yang tersedia.
Dalam laporan yang sama, McKinsey memperkirakan bahwa bahkan di tahun 2050 dunia masih akan bergantung pada energi fosil antara 41 persen hingga 55 persen dari konsumsi global. Artinya, kita punya ruang waktu untuk melakukan transisi yang cerdas - bukan dengan tergesa-gesa meninggalkan fosil, tetapi dengan mengubahnya menjadi jembatan menuju masa depan bersih.
Indonesia dapat menjadikan gas alam sebagai bahan bakar transisi, sambil secara perlahan menyiapkan sistem energi berbasis terbarukan. Batu bara yang selama ini menjadi tulang punggung devisa nasional dapat diarahkan pada hilirisasi untuk menghasilkan gas sintetis, amonia, atau bahan baku industri kimia rendah karbon.
Dengan demikian energi lama tidak dibuang, tetapi ditransformasi menjadi bagian dari ekonomi baru. Transisi energi pun menjadi transisi ekonomi yang menciptakan nilai tambah, bukan sekadar mengganti sumber daya.
Tapi pembangunan badan energi hijau tidak cukup hanya dengan kebijakan dan proyek. Di belakang badan energi hijau ini perlu digerakkan oleh sumber daya manusia yang memiliki kesamaan visi dan terampil.
Di balik setiap turbin angin dan panel surya ada pekerja yang harus dilatih ulang, insinyur yang perlu dilibatkan, ilmuwan yang harus diberdayakan. Lebih dari 250 ribu pekerja di industri batu bara perlu diarahkan ke industri baru agar transisi ini tidak melahirkan pengangguran massal.
Energi hijau yang hanya mengganti alat tanpa membangun manusia hanyalah pergantian teknologi, bukan pembangunan. Pendidikan vokasi energi, riset di universitas, dan kemitraan teknologi dengan industri harus ditempatkan sebagai prioritas.
Undang‑Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi menetapkan bahwa sumber daya energi adalah kekayaan alam yang dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pasal 2 UU tersebut menegaskan pengelolaan energi harus berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi, keadilan, peningkatan nilai tambah, berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, ketahanan nasional, serta keterpaduan dan mengutamakan kemampuan nasional.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional menegaskan target minimal pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional.
Dan lebih jauh lagi, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik mempercepat pengembangan EBT untuk sektor listrik.
Meski demikian, regulasi yang mengatur secara khusus tentang energi baru dan terbarukan secara komprehensif masih dalam proses penyusunan melalui Rancangan Undang‑Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBT). Maka, langkah transisi ini bukan berkutat dalam aspek teknis dan investasi, tetapi juga harus berpijak pada kerangka hukum yang kokoh.
Tantangan terbesar justru ada di pembiayaan. Dunia menyadari bahwa transisi energi adalah investasi terbesar abad ini. Indonesia membutuhkan ratusan miliar dolar untuk mencapai target net-zero pada 2060.
Namun di tengah suku bunga global yang tinggi, modal menjadi mahal, dan risiko politik membuat investor ragu. Di sinilah pemerintah harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai enabler.
Subsidi energi fosil yang saat ini mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun perlu diarahkan ulang ke investasi hijau: pembangunan pembangkit surya di wilayah timur Indonesia, penguatan transmisi lintas pulau, atau dukungan riset penyimpanan energi nasional.
Pembiayaan kreatif juga harus diciptakan melalui instrumen seperti obligasi hijau, perdagangan karbon, dan skema pembiayaan campuran (blended finance) yang mempertemukan dana publik dan swasta.
Indonesia memiliki kekuatan moral di mata dunia sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga dan populasi muda yang haus inovasi serta daya tawar untuk menjadi laboratorium transisi hijau yang adil dan inklusif.
Dunia kini mencari model transisi yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang. Indonesia bisa menjadi contoh jika negara ini mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Dalam makna yang lebih luas, energi hijau bukan sekadar perubahan teknologi, tetapi revolusi peradaban. Ia menuntut kita untuk berpikir dalam jangka panjang, melampaui horizon politik lima tahunan.
Energi hijau adalah tentang masa depan yang ingin kita wariskan: apakah Indonesia tetap menjadi eksportir bahan mentah, atau menjadi penggerak industri hijau Asia? Ketika energi bersih menjadi sumber daya strategis, industri ini berpotensi untuk memperkuat rupiah, menurunkan biaya hidup, dan meningkatkan daya saing industri nasional.
Kini arah energi hijau Indonesia bukan hanya soal membangun pembangkit listrik, tetapi soal membangun peradaban baru. Jiwa yang sadar bahwa energi bersih adalah bagian dari martabat bangsa, dan badan yang kuat yang mewujudkannya melalui kebijakan, industri, dan manusia.
Jika lagu "Indonesia Raya" dulu menjadi seruan kemerdekaan politik, kini ia bisa menjadi seruan kemerdekaan energi. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Lirik lagu ini bisa diartikan sebagai berikut, bangun kesadarannya, bangun infrastrukturnya. Bangun ilmunya, bangun industrinya. Bangun keyakinannya, bangun kekuatannya.
Karena hanya dengan keduanya, jiwa dan badan yang bergerak seiring maka Indonesia bisa berdiri tegak di era baru ekonomi hijau. Saat itu tiba, energi bukan lagi beban fiskal, melainkan sumber kemakmuran nasional. Dan Indonesia tidak hanya menjadi penonton dari revolusi energi global, tetapi salah satu arsiteknya.
(miq/miq)

 3 hours ago
3
3 hours ago
3














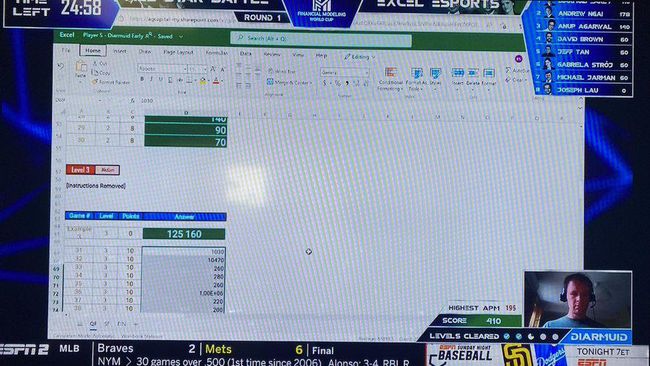

















:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5273598/original/029668700_1751637513-WhatsApp_Image_2025-07-04_at_8.55.48_PM.jpeg)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4713389/original/012163500_1704983411-WhatsApp_Image_2024-01-11_at_21.21.33.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4741002/original/036562200_1707726174-6_Gaya_Ceria_Ria_Ricis_dengan_Outfit_Cerah_saat_Liburan_di_Eropa__5_.jpg)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5272514/original/002039600_1751554236-WhatsApp_Image_2025-07-03_at_9.46.56_PM.jpeg)







