Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Demo besar-besaran para pengemudi ojek online (20 Mei 2025) lalu, kembali membuka mata kita pada kenyataan getir ekonomi digital: bahwa di balik kemudahan layanan dan geliat aplikasi, ada ketidakpastian dan ketimpangan yang dalam. Para pengemudi yang selama ini disebut "mitra" turun ke jalan bukan karena tak mau bekerja, tapi karena sistem yang mereka jalani tak memberi ruang untuk suara, apalagi tawar-menawar.
Di tengah hiruk-pikuk pembangunan ekonomi digital, ada suara-suara yang mulai pelan: suara pekerja yang terus bergerak tanpa kontrak, tanpa jaminan sosial, dan tanpa perlindungan hukum. Mereka adalah wajah baru kelas pekerja Indonesia di era gig economy: berjaket aplikator, terhubung ke internet, bekerja di jalanan atau dari rumah, siang malam mengejar insentif dan bintang lima. Dalam dokumen, mereka disebut mitra. Namun dalam kenyataan, mereka tunduk pada logika sistem yang tak bisa mereka tawar, apalagi kendalikan.
Kita sering menyebut ini era fleksibilitas. Tapi seiring waktu, fleksibilitas yang dibanggakan berubah menjadi keterikatan baru. Platform digital menciptakan ilusi kebebasan bekerja, padahal di baliknya tersembunyi struktur kekuasaan yang lebih halus dan menindas. Algoritma menjadi atasan yang tak terlihat namun mutlak. Ini bukan lagi sekadar soal kerja, ini soal relasi kuasa.
Ketimpangan di Era Platform
Ekonom Yunani Yanis Varoufakis (2023) menyebut fenomena ini sebagai tekno-feodalisme. Di bawah sistem ini, pemilik algoritma bukan sekadar pengusaha; mereka adalah tuan tanah digital yang mengatur siapa mendapat pekerjaan, berapa besar bayarannya, dan bagaimana seseorang dinilai. Semuanya tanpa transparansi, tanpa dialog, tanpa hak keberatan. Pekerja platform menjadi penyewa algoritmik dalam sistem yang sepenuhnya dikendalikan kode.
Di Indonesia, situasinya menjadi lebih kompleks. Mayoritas pekerja digital berada dalam sektor informal. Menurut laporan CELIOS (2025), hanya 0,5 persen dari mereka yang terdaftar dalam skema jaminan sosial. Tidak ada cuti sakit, tidak ada perlindungan kecelakaan, tidak ada kepastian pendapatan. Ketika aplikasi mati, penghasilan pun lenyap.
Jika kita terus membiarkan sistem ini berjalan tanpa intervensi, maka ekonomi digital bukan akan menjadi lokomotif kemajuan, melainkan penggali jurang ketimpangan yang baru. Dalam masyarakat yang digital, keadilan menjadi semakin mendesak.
Desain Kebijakan Inklusif
Beberapa negara telah bergerak. Belgia, misalnya, menerapkan Employment Deal tahun 2022 yang menetapkan praduga hukum bagi pekerja platform. Jika seorang pengemudi atau kurir memenuhi tiga dari delapan indikator ketergantungan; misalnya tidak bebas menentukan tarif, tidak bisa memilih waktu kerja, atau tidak bekerja lintas platform; maka ia dianggap pekerja formal. Beban pembuktian ada pada perusahaan, bukan pekerja.
Kebijakan ini tidak mematikan industri digital. Meski jumlah proyek investasi asing di Belgia turun 4 persen, lapangan kerja justru tumbuh 16 persen pada tahun yang sama. Sektor teknologi informasi tetap tumbuh, membuktikan bahwa perlindungan bisa berjalan seiring dengan inovasi.
Indonesia tentu memiliki tantangannya sendiri. Struktur ekonomi kita didominasi sektor informal. Banyak platform digital masih dalam tahap tumbuh. Tapi prinsip dasarnya tetap berlaku: bahwa fleksibilitas kerja tidak boleh mengorbankan hak dasar. Kita perlu merancang ulang sistem, tidak sekadar menyesuaikan diri pada teknologi, melainkan membentuk teknologi yang melayani nilai-nilai keadilan.
Audit dan Regulasi Algoritma
Untuk menghadapi tekno-feodalisme, negara tidak cukup hadir sebagai penonton atau fasilitator. Ia harus menjadi arsitek dari pasar kerja digital yang adil dan beradab. Itu dimulai dengan pengakuan hukum terhadap pekerja digital. Mereka harus memiliki hak atas jaminan sosial, asuransi kecelakaan, dan sistem keberatan jika dirugikan algoritma.
Model yang dapat dikembangkan adalah skema jaminan sosial hybrid, di mana kontribusi dibagi antara pekerja, platform, dan negara, dengan subsidi untuk kelompok berpenghasilan rendah. Platform yang patuh diberi insentif fiskal dan pengakuan publik melalui sertifikasi kerja layak digital. Semua ini tak hanya melindungi pekerja, tapi juga memberi kejelasan bagi ekosistem industri.
Yang paling penting, Indonesia perlu membangun sistem audit algoritma. Algoritma yang mengatur hidup jutaan orang tak boleh menjadi kotak hitam yang tak tersentuh. Harus ada regulasi yang mewajibkan platform membuka cara kerja sistem penilaian, distribusi kerja, dan penentuan tarif. Harus ada lembaga independen yang mengawasi, dan pekerja harus diberi hak untuk tahu serta menantang keputusan algoritma yang merugikan mereka.
Tanpa audit algoritma, relasi antara platform dan pekerja akan terus timpang. Dan tanpa kehadiran negara sebagai penyeimbang, revolusi digital akan berjalan tanpa arah moral. Kita tidak sedang menolak teknologi; kita sedang menolak ketidakadilan yang disembunyikan dalam barisan kode.

 6 hours ago
4
6 hours ago
4








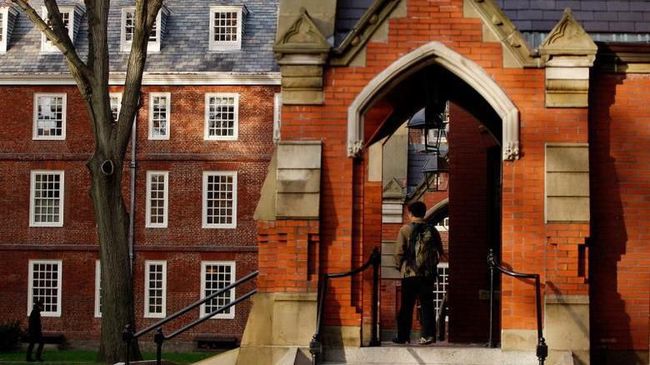








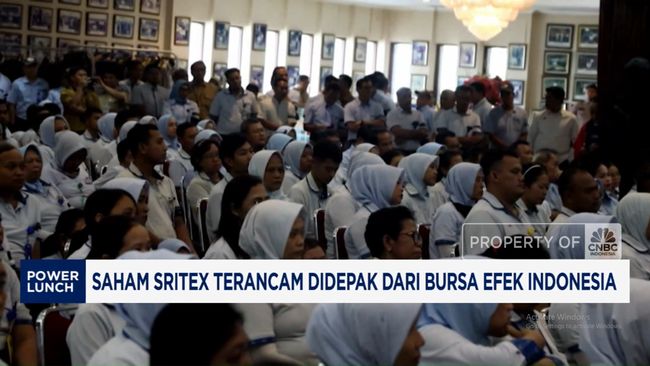












:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5106825/original/004690100_1737626093-WhatsApp_Image_2025-01-23_at_15.17.14.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5060424/original/012183800_1734756388-1734752130220_tips-puasa-untuk-anak.jpg)



:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1557398/original/000879000_1491379838-20170405-Panin-bank-bergabung-dalam-RDN-AY2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2249518/original/029795300_1528876812-clouds-mosque-muslim-87500.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4012157/original/011961400_1651313934-20220430-_Gerbang_Tol_Cikampek-1.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3081755/original/098010500_1584692954-20200320-Suasana-Salat-Jumat-di--Masjid-Agung-Al-Azhar-Jakarta-2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4294815/original/095852200_1674030831-IMG-20220605-WA0000.jpg)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1619105/original/061499300_1496997418-ramadan-main.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3977835/original/066021800_1648524608-pexels-ahmed-aqtai-2233416_1_.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5060939/original/058494500_1734788980-2024121_Indonesia_vs_Filipina-10.JPG)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5140557/original/014077100_1740215641-Key_Visual_Shopee_Big_Ramadan_Sale.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2224127/original/003015200_1527048124-serenity-banner-kl-kuala-lumpur-putrajaya-mosque-sunrise-masjid-reflections-limited-edition-print-paul-reiffer-fine-art-malaysia-morning.jpg)