Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Perang dagang memasuki tahap baru saat saling balas pengenaan tarif terjadi antara Amerika Serikat dan China. Keadaan bertambah panas tatkala Pemerintah AS kembali menaikkan tarif setelah beberapa waktu terjadi pendinginan suasana.
Besaran tarif yang dikenakan melonjak hingga 245% bagi sejumlah produk yang diimpor dari China. Tampaknya kondisi tarik ulur ini akan terus berlangsung hingga tiga bulan ke depan atau 90 hari masa penundaan pengenaan tarif diberlakukan.
Dalam negosiasi, tarik ulur maupun cooling down merupakan bagian yang akan saling berganti sembari menyusun berbagai alternatif tawaran yang diajukan. Bagi China masa cooling down berarti kalkulasi ulang serta penyusunan berbagai skenario termasuk alternatif relokasi industri ke negara lain.
Begitu juga dengan AS, jeda waktu yang ada merupakan kesempatan untuk menghitung ulang volume produk impor yang dibutuhkan serta potensi perpindahan pemasok dari satu negara ke negara lain. Untuk memuluskan skenario yang ada, AS saat ini jelas membagi pemasok dalam dua kelompok, yaitu pemasok dari pabrikan di China dan negara-negara non-China.
Aksi saling balas tarif antara AS dan China akan mengisi topik teratas pemberitaan di dunia hingga negosiasi dengan negara-negara pemasok non-China mencapai kesepakatan. Mengapa harus menunggu kesepakatan dengan negara-negara non-China? Hal ini tentu saja untuk meneguhkan posisi AS dalam negosiasi.
Tarik ulur tersebut akan terus dilakukan dengan tujuan agar tarif yang dikenakan nantinya memberikan dampak paling minimalis bagi perekonomian AS serta dapat mengurangi besaran defisit yang terjadi selama ini. AS berusaha agar produk-produk yang mereka impor berlaku resiprositas sehingga menjadi penyeimbang dalam perdagangan internasional.
Target perang dagang sebenarnya sudah amat jelas, yaitu adanya pengurangan defisit perdagangan antara AS dengan seluruh negara-negara di dunia. Pengurangan defisit akan membuka lapangan pekerjaan baru di AS yang bermakna tumbuhnya ekonomi khususnya bagi AS. Bagaimana dengan negara mitra dagang AS?
Pertumbuhan ekonomi pun dapat dinikmati sebagai dampak dari pengenaan tarif. Tentu saja jika produk imbal dagang yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan negara mitra dagang tanpa mengganggu pasar domestik negara tersebut.
Sebagai gambaran sebuah negara dengan swasembada produk unggas jelas akan terganggu pasar domestik negara tersebut jika ingin mengimpor produk unggas dari AS. Seandainya hal ini terjadi bukannya pertumbuhan ekonomi yang diraih pascaperang tarif namun malah kerugian akibat rusaknya pasar di dalam negeri.
Global supply chain atau rantai pasok global memungkinkan terjadinya perbedaan lokasi antara dimana sebuah merek didaftarkan dan di mana merek tersebut diproduksi. Oleh sebab itu, keberadaan pemasok untuk membuat sebuah produk dapat tersebar di seluruh dunia meskipun merek produk tersebut didaftarkan pada satu negara.
Sebuah produk dapat dibuat di manapun dengan biaya serendah mungkin, hanya faktor yang berkaitan dengan perpajakan yang menjadikan output dari proses produksi memiliki harga yang bervariasi.
Pengenaan tambahan bea masuk jelas membuat harga produk dari sebuah negara meningkat dan menjadi tidak kompetitif apabila bersaing dengan produk negara lain. Solusi yang kemudian diambil agar harga jual tidak terlalu berubah yakni dengan melakukan relokasi industri ke negara lain yang memiliki tarif yang lebih rendah.
Perang dagang jilid kedua saat ini memiliki konsekuensi yang mirip dengan yang terjadi pada perang dagang jilid pertama. Dampak pengenaan tarif bea masuk tambahan akan membuat industri manufaktur pindah dari suatu negara ke negara lain yang memiliki keunggulan komparatif khususnya dalam tarif yang lebih rendah. Salah satu negara yang paling terdampak atas pengenaan tarif tersebut adalah China.
Sebagai pusat produksi dunia, China menjadi sasaran utama pengenaan tarif oleh AS. Pada 2024, China mengekspor sekitar $440 miliar dolar ke AS dan sebagai timbal baliknya China hanya mengimpor sekitar $140 miliar dolar dari AS.
Selisih luar biasa tersebut merupakan nilai yang susah dipenuhi oleh China jika AS menuntut untuk mengurangi defisit yang terjadi. China memiliki keunggulan secara kompetitif pada sejumlah produk hingga mustahil apabila pengurangan defisit menjadi tujuan dari pengenaan bea masuk tambahan.
Berbeda dengan negara non-China yang memiliki alternatif komoditas berupa produk-produk persenjataan sebagai cara untuk menyeimbangkan neraca dagang. Bagi AS, akses untuk teknologi tinggi seperti persenjataan tertutup bagi China.
Sehingga menjadi lebih terbatas lagi alternatif yang bisa dipilih oleh China untuk mengurangi defisit. Salah satu cara yang bisa dilakukan tentu saja akan sama dengan yang terjadi pada perang dagang jilid pertama, yaitu eksodusnya industri ke luar China.
Bagi negara pemasok non-China, perang dagang kali ini bisa menjadi berkah meskipun terdapat peluang suatu negara tidak mendapat manfaat sama sekali. Saat ini setiap negara pasti berusaha untuk memenuhi keinginan pihak AS dalam pengurangan defisit perdagangan, dan kompensasi yang diharapkan oleh setiap negara adalah penurunan tarif bea masuk.
Semakin rendah tarif bea masuk yang dikenakan maka semakin menarik suatu negara di mata investor, apalagi jika negara tersebut memiliki keunggulan berupa tingkat upah buruh yang rendah.
Bagaimana dengan Indonesia? era perang dagang jilid pertama diakui atau tidak kita telah kalah langkah dengan negara tetangga kita. Eksodus industri dari China pasca pengenaan tarif saat itu mayoritas ternyata beralih ke Vietnam, Thailand, Malaysia, Meksiko, dan India. Hanya sedikit dari pabrikan yang mengalihkan lokasi produksinya ke Indonesia.
Pada perang dagang jilid kedua ini seharusnya Indonesia lebih siap dibandingkan dengan jilid pertama. Agenda pengurangan defisit harus dijadikan pedoman utama bagi Indonesia untuk bisa meraih limpahan pabrikan yang mengalihkan lokasi produksi. Dalam pemilihan komoditas yang akan dijadikan alat tawar menawar pun perlu kehati-hatian agar jangan sampai industri di dalam negeri terganggu.
AS memiliki keunggulan dalam produksi pertanian, peternakan, serta permesinan termasuk produk-produk persenjataan. Hal ini selayaknya menjadi acuan untuk memilih komoditas yang sesuai. Produk-produk persenjataan adalah daftar prioritas yang harus dipilih untuk mengurangi defisit yang terjadi.
Alasan mengapa produk persenjataan dipilih karena nilai produk tersebut cukup signifikan dan bagi pihak AS industri persenjataan adalah salah satu sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu beberapa kali Indonesia juga telah mengajukan penawaran untuk mengakuisisi sejumlah persenjataan dari AS sejak beberapa tahun lalu meskipun saat ini posisinya masih "digantung".
Akuisisi produk-produk persenjataan dari AS dapat dijadikan peluang bagi Indonesia untuk melakukan imbal balik berupa penambahan ekspor baja ke AS. Hal ini akan meningkatkan kapasitas produksi baja di Indonesia termasuk pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi penduduk di Indonesia.
Bagaimana respons negara tetangga terkait tawaran produk persenjataan sebagai komoditas pengurang defisit perdagangan? Beberapa negara di kawasan Asean menyatakan sanggup untuk membeli produk-produk tersebut.
Filipina telah menyatakan keinginannya untuk membeli produk persenjataan dengan tujuan untuk mengurangi defisit termasuk pula Vietnam. Vietnam yang selama ini nyaris tidak pernah menggunakan persenjataan produksi AS pun akhirnya menyatakan kesanggupannya membeli produk persenjataan dari AS sebagai cara untuk mengurangi defisit yang terjadi.
Pemilihan produk nonpersenjataan atau permesinan mungkin malah dianggap sebagai langkah basa-basi dan tidak serius dalam negosiasi kali ini. Sebagai ilustrasi untuk produk-produk pertanian dan peternakan apabila akan dijadikan sebagai komoditas penyeimbang defisit akan berimplikasi terhadap volume dan negara mitra dagang Indonesia.
Kebutuhan daging sapi misalnya, ketika akan dijadikan alat tawar maka volume yang akan diimpor tidak mungkin akan naik secara signifikan ditambah lagi sudah ada negara lain yang menjadi pemasok utama daging sapi bagi Indonesia yaitu Australia.
Contoh lain adalah kebutuhan kedelai, setiap tahunnya Indonesia mengimpor kedelai sekitar $1,2 miliar dari AS (85% dari kebutuhan kedelai tanah air). Dengan surplus perdagangan yang mencapai rata-rata $12 miliar per tahunnya, apabila dikonversi ke peningkatan pembelian kedelai akan setara dengan kebutuhan selama 10 tahun. Hal ini yang mungkin dianggap oleh negosiator dari pihak AS sebagai tawaran yang kurang serius.
Indonesia masih memiliki kesempatan untuk menyempurnakan tawaran yang diajukan. Diakui atau tidak, melakukan negosiasi tarif dengan AS adalah pilihan paling rasional untuk dilakukan meski seolah-olah posisi kita berada lebih rendah.
Memilih alternatif lain berupa mengalihkan tujuan ekspor ke negara selain AS meskipun secara teori mungkin dilakukan namun faktanya tidak semudah yang dibayangkan. Kita akan dihadapkan pada proses awal membuka pasar di suatu negara yang bisa dipastikan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Belum lagi permasalahan baru berupa persaingan dengan produk-produk sejenis dari negara lain khususnya produk buatan China.
(miq/miq)

 5 hours ago
2
5 hours ago
2

















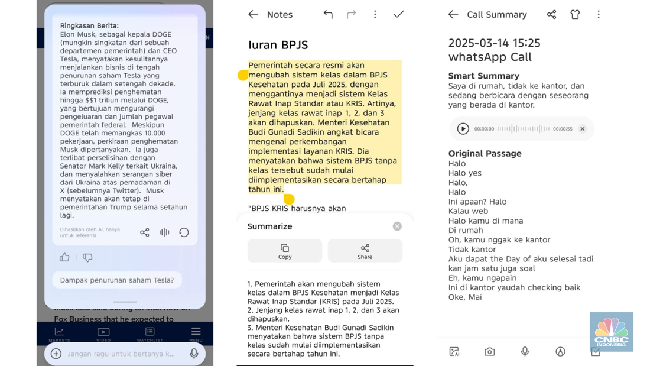








:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5106825/original/004690100_1737626093-WhatsApp_Image_2025-01-23_at_15.17.14.jpeg)



:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5060424/original/012183800_1734756388-1734752130220_tips-puasa-untuk-anak.jpg)





:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5051207/original/080163400_1734234398-pexels-bertellifotografia-29509460.jpg)





:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1557398/original/000879000_1491379838-20170405-Panin-bank-bergabung-dalam-RDN-AY2.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4012157/original/011961400_1651313934-20220430-_Gerbang_Tol_Cikampek-1.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2249518/original/029795300_1528876812-clouds-mosque-muslim-87500.jpg)